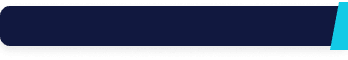Cari modal kompetisi, nodong dana CSR ke mana lagi?

Cari modal kompetisi, nodong dana CSR ke mana lagi?
A
A
A
Sindonews.com - PSSI tak lama lagi bakal melakukan verifikasi tentang kelayakan klub mengikuti liga unifikasi musim 2014. Dua minggu lagi klub-klub bakal diperiksa dan dinilai apakah mereka tetap tampil di kompetisi yang tetap bernama Indonesia Super League (ISL), atau bakal turun kasta.
Tapi, di sini saya tak akan membahas lebih jauh soal verifikasi yang tidak melibatkan AFC tersebut. Hasil verifikasi bisa gampang diakali dengan berbagai cara untuk meloloskan klub ke kompetisi. Pengalaman membuktikan verifikasi ini hanya sekadar formalitas.
Terlepas dari verifikasi, yang menarik adalah bagaimana klub-klub berupaya menghidupi dirinya dengan kondisi finansial yang mengenaskan. Banyak klub yang belum memiliki duit sebagai bekal kompetisi padahal kick-off tinggal dua bulan lagi.
Selalu ada klub yang mengalami krisis finansial tiap musimnya sangat wajar jika melihat sistem penggalian dana. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilarang campur tangan di klub professional, klub-klub dituntut secara mandiri untuk menjalankan operasional tim.
Jika diambil rata-rata, dana terbesar alias 80% lebih adalah dari sponsor. Sisanya datang dari penjualan tiket dan sumber lain. Persoalannya, bagi klub yang tak mempunyai investor besar, pencarian sponsor sangat sulit dan terpaksa memakai ‘hukum preman’.
Eks klub perserikatan yang dulunya tergantung dana APBD, sebenarnya tidak sepenuhnya lepas dari campur tangan pemerintah daerah. Fungsi pemerintah kini telah berubah dan tidak lagi menyokong dana secara langsung dengan uang rakyat lewat APBD.
Pemerintah daerah sekarang lebih bertugas sebagai ‘preman’ dengan menodong perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Entah perusahaan tersebut berniat menjadi sponsor atau tidak, yang jelas sebisa mungkin memberikan kontribusi untuk klub.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sasaran tembak untuk menghidupi klub. Saya tidak perlu menyebut nama klubnya, yang pasti salah satu klub di Jawa Timur ada yang menodong perusahaan untuk menyetor dana antara Rp500 juta hingga Rp800 juta untuk menghidupi klub.
Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak bisa terus-terusan memberikan dana CSR-nya tiap tahun secara gratis. Ini masuk akal karena perusahaan harus tetap bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang selama ini sudah menjadi target CSR.
Kalau dulu APBD dilarang dengan alasan duitnya lebih baik untuk pembangunan, apa bedanya dengan sekarang? Dana CSR yang disedot klub juga mengurangi jatah masyarakat untuk menerima dana pembangunan. Bedanya hanya pada siapa pemilik dana tersebut.
Mungkin satu atau dua tahun, sistem pencarian dana seperti ini masih berhasil. Tapi tentu bukan untuk jangka panjang. Sejumlah klub kini mulai merasakan seretnya memeras dana CSR. Sebab perusahaan juga berpikir dua kali untuk mengeluarkan uang ratusan juta dengan tujuan yang tidak jelas.
Bolehlah kalau produk perusahaan tersebut memang pangsa pasarnya sesuai dengan supporter sepakbola. Tapi kalau produknya tidak membutuhkan promosi lewat sepakbola, jelas tidak ada benefit apa-apa yang diperoleh. Hubungan mutualis antara klub dan sponsor pun tak terjadi. Klub senang dapat uang, perusahaan pusing bukan kepalang.
Kondisi inilah yang semakin memperlihatkan bahwa profesionalisme klub Indonesia adalah semu. Mungkin sebuah klub terlihat sehat saat verifikasi sebelum kompetisi dimulai. Tapi tidak ada jaminan kondisi itu akan terus berlanjut hingga pertengahan dan akhir kompetisi.
Klub-klub tanpa investor kakap belum bisa menjawab kontinuitas kesehatan finansial. Di awal musim masih segar bugar karena dana masih tersedia. Tapi di akhir musim dan menyambut musim baru, manajemen klub harus menyediakan banyak obat sakit kepala karena sulitnya mencari dana. Musim baru ibarat hantu.
PSSI yang tak pernah benar-benar serius menjalankan verfikasi, semakin memperburuk situasi. Saya sendiri masih yakin jika verifikasi tersebut dilakukan dengan professional mutlak, maka hanya dua-tiga klub saja yang bisa tampil di kompetisi level satu. (*)
Tapi, di sini saya tak akan membahas lebih jauh soal verifikasi yang tidak melibatkan AFC tersebut. Hasil verifikasi bisa gampang diakali dengan berbagai cara untuk meloloskan klub ke kompetisi. Pengalaman membuktikan verifikasi ini hanya sekadar formalitas.
Terlepas dari verifikasi, yang menarik adalah bagaimana klub-klub berupaya menghidupi dirinya dengan kondisi finansial yang mengenaskan. Banyak klub yang belum memiliki duit sebagai bekal kompetisi padahal kick-off tinggal dua bulan lagi.
Selalu ada klub yang mengalami krisis finansial tiap musimnya sangat wajar jika melihat sistem penggalian dana. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilarang campur tangan di klub professional, klub-klub dituntut secara mandiri untuk menjalankan operasional tim.
Jika diambil rata-rata, dana terbesar alias 80% lebih adalah dari sponsor. Sisanya datang dari penjualan tiket dan sumber lain. Persoalannya, bagi klub yang tak mempunyai investor besar, pencarian sponsor sangat sulit dan terpaksa memakai ‘hukum preman’.
Eks klub perserikatan yang dulunya tergantung dana APBD, sebenarnya tidak sepenuhnya lepas dari campur tangan pemerintah daerah. Fungsi pemerintah kini telah berubah dan tidak lagi menyokong dana secara langsung dengan uang rakyat lewat APBD.
Pemerintah daerah sekarang lebih bertugas sebagai ‘preman’ dengan menodong perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Entah perusahaan tersebut berniat menjadi sponsor atau tidak, yang jelas sebisa mungkin memberikan kontribusi untuk klub.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sasaran tembak untuk menghidupi klub. Saya tidak perlu menyebut nama klubnya, yang pasti salah satu klub di Jawa Timur ada yang menodong perusahaan untuk menyetor dana antara Rp500 juta hingga Rp800 juta untuk menghidupi klub.
Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak bisa terus-terusan memberikan dana CSR-nya tiap tahun secara gratis. Ini masuk akal karena perusahaan harus tetap bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar atau pihak-pihak yang selama ini sudah menjadi target CSR.
Kalau dulu APBD dilarang dengan alasan duitnya lebih baik untuk pembangunan, apa bedanya dengan sekarang? Dana CSR yang disedot klub juga mengurangi jatah masyarakat untuk menerima dana pembangunan. Bedanya hanya pada siapa pemilik dana tersebut.
Mungkin satu atau dua tahun, sistem pencarian dana seperti ini masih berhasil. Tapi tentu bukan untuk jangka panjang. Sejumlah klub kini mulai merasakan seretnya memeras dana CSR. Sebab perusahaan juga berpikir dua kali untuk mengeluarkan uang ratusan juta dengan tujuan yang tidak jelas.
Bolehlah kalau produk perusahaan tersebut memang pangsa pasarnya sesuai dengan supporter sepakbola. Tapi kalau produknya tidak membutuhkan promosi lewat sepakbola, jelas tidak ada benefit apa-apa yang diperoleh. Hubungan mutualis antara klub dan sponsor pun tak terjadi. Klub senang dapat uang, perusahaan pusing bukan kepalang.
Kondisi inilah yang semakin memperlihatkan bahwa profesionalisme klub Indonesia adalah semu. Mungkin sebuah klub terlihat sehat saat verifikasi sebelum kompetisi dimulai. Tapi tidak ada jaminan kondisi itu akan terus berlanjut hingga pertengahan dan akhir kompetisi.
Klub-klub tanpa investor kakap belum bisa menjawab kontinuitas kesehatan finansial. Di awal musim masih segar bugar karena dana masih tersedia. Tapi di akhir musim dan menyambut musim baru, manajemen klub harus menyediakan banyak obat sakit kepala karena sulitnya mencari dana. Musim baru ibarat hantu.
PSSI yang tak pernah benar-benar serius menjalankan verfikasi, semakin memperburuk situasi. Saya sendiri masih yakin jika verifikasi tersebut dilakukan dengan professional mutlak, maka hanya dua-tiga klub saja yang bisa tampil di kompetisi level satu. (*)
(aww)