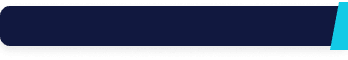Antara Filsafat dan World Cup (2 - Bersambung)

Antara Filsafat dan World Cup (2 - Bersambung)
A
A
A
Oleh : K.Y. Karnanta (*)
Yang menarik, dari sederetan nama filsuf dalam peta filsafat barat, Prancis banyak melahirkan filsuf “kanan” sedangkan Jerman identik dengan “yang kiri” atau kontroversial dan anti kemapanan. Pertanyaannya, di manakah letak korelasi antara filsafat ilmu pengetahuan dengan sepak bola?
Filosofi Bola
Ada dua aspek intrinsik utama dalam sepak bola, yakni kualitas pemain dan kualitas permainan. Aspek yang pertama berkenaan dengan bakat dan kemampuan individu. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan kolektivitas, yang mana dibutuhkan pemikiran dan strategi jitu untuk mengorganisasikan sebuah tim. Sinergi dan totalitas antara keduanya mutlak dibutuhkan agar organisasi permainan tim seimbang dan merata, hingga mampu memunculkan permainan maksimalnya.
Namun ternyata tidak mudah mewujudkan totalitas tersebut. Sebuah tim biasanya unggul di salah satu aspek namun lemah di aspek lainnya. Dalam konteks Piala Dunia 2014, Brazil layak disebut sebagai tim yang merepresentasikan kecenderungan pertama, yakni unggul materi pemain.
Seperti banyak diketahui, sepak bola bagi Brazil adalah ''agama kedua” Sang legendaris Pele mengatakan bahwa rakyat Brazil yang rata-rata hidup dengan ekonomi pas-pasan, menjadikan sepak bola sebagai “jalan tol” untuk mendapat uang.
Tak heran, lanjut Pele, pemain-pemain fenomenal dari negara pemenang Piala Dunia terbanyak ini, seperti Neymar, David Luiz, Dani Alves dan lain-lain, rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu. Bintang-bintang ini justru berkenalan dengan sepak bola di jalanan atau pinggir pantai, namun semakin terasah karenanya. Begitu kuat sepak bola mengalir dalam darah orang Brasil dan menjadi semacam volk-geist (identitas budaya) turun-temurun, hingga bakat alam terbangun dengan sendirinya.
Bagaimana dengan Eropa? Tim-tim Eropa tidak seberuntung Brasil dalam hal kuantitas maupun kualitas pemain. Namun meski dengan bakat “pas-pasan”, tim-tim Eropa terus berupaya dan terbukti mampu menjadi pesaing sengit. Ini dikarenakan tim Eropa mewarisi tradisi berpikir cermat, kritis dan inovatif.
Dengan mengutak-atik sepak bola sebagai “objek pemikiran”, lahirlah gaya permainan yang sistematis, agresif, cepat dan efisien. Gaya-gaya permainan ini kemudian termanifestasikan dalam bentuk kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah sepak bola, dan hingga kini masih menjadi ciri di liga-liga Eropa.
Bukti nyata, total football Belanda, atau kick and rush Inggris. Ada pun Italia dengan sepak bola pasif ala Catenaccio yang mengandalkan serangan balik, namun terbukti efektif mengantarkannya merebut tiga kali trofi Piala Dunia. Determinasi tinggi juga diperagakan oleh tim-tim semisal Jerman dan Prancis. Kolektivitas dan efisiensi permainan secara gemilang ditunjukkan oleh negeri para filsuf kuno, Yunani, dengan menjuarai Piala Eropa 2004 lalu, yang kini melaju di babak 16 besar
Ini jelas berbeda dengan gaya permainan tim-tim asal Amerika latin semisal Brazil dan Argentina yang cenderung memainkan jogo bonito -sebuah estetika bermain sepak bola yang menghibur dengan gerakan “menari-nari” di lapangan. Meski tidak memiliki tradisi filsafat yang kuat, namun tim-tim Amerika Latin mampu menggabungkan kultur tarian mereka dengan olahraga.
Maka jika dibandingkan, tak heran dribbling Thomas Mueller tidak seatraktif Lionel Messi. Van Persie tak selincah Neymar. Namun sedikit saja Mueller dan Persie mempunyai peluang, naluri gol pemain sekolahan ini tak kalah mematikan dengan dua pemain Brazil tersebut.
(*) Penulis adalah dosen di Universitas Airlangga dan Universitas Ciputra
Yang menarik, dari sederetan nama filsuf dalam peta filsafat barat, Prancis banyak melahirkan filsuf “kanan” sedangkan Jerman identik dengan “yang kiri” atau kontroversial dan anti kemapanan. Pertanyaannya, di manakah letak korelasi antara filsafat ilmu pengetahuan dengan sepak bola?
Filosofi Bola
Ada dua aspek intrinsik utama dalam sepak bola, yakni kualitas pemain dan kualitas permainan. Aspek yang pertama berkenaan dengan bakat dan kemampuan individu. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan kolektivitas, yang mana dibutuhkan pemikiran dan strategi jitu untuk mengorganisasikan sebuah tim. Sinergi dan totalitas antara keduanya mutlak dibutuhkan agar organisasi permainan tim seimbang dan merata, hingga mampu memunculkan permainan maksimalnya.
Namun ternyata tidak mudah mewujudkan totalitas tersebut. Sebuah tim biasanya unggul di salah satu aspek namun lemah di aspek lainnya. Dalam konteks Piala Dunia 2014, Brazil layak disebut sebagai tim yang merepresentasikan kecenderungan pertama, yakni unggul materi pemain.
Seperti banyak diketahui, sepak bola bagi Brazil adalah ''agama kedua” Sang legendaris Pele mengatakan bahwa rakyat Brazil yang rata-rata hidup dengan ekonomi pas-pasan, menjadikan sepak bola sebagai “jalan tol” untuk mendapat uang.
Tak heran, lanjut Pele, pemain-pemain fenomenal dari negara pemenang Piala Dunia terbanyak ini, seperti Neymar, David Luiz, Dani Alves dan lain-lain, rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu. Bintang-bintang ini justru berkenalan dengan sepak bola di jalanan atau pinggir pantai, namun semakin terasah karenanya. Begitu kuat sepak bola mengalir dalam darah orang Brasil dan menjadi semacam volk-geist (identitas budaya) turun-temurun, hingga bakat alam terbangun dengan sendirinya.
Bagaimana dengan Eropa? Tim-tim Eropa tidak seberuntung Brasil dalam hal kuantitas maupun kualitas pemain. Namun meski dengan bakat “pas-pasan”, tim-tim Eropa terus berupaya dan terbukti mampu menjadi pesaing sengit. Ini dikarenakan tim Eropa mewarisi tradisi berpikir cermat, kritis dan inovatif.
Dengan mengutak-atik sepak bola sebagai “objek pemikiran”, lahirlah gaya permainan yang sistematis, agresif, cepat dan efisien. Gaya-gaya permainan ini kemudian termanifestasikan dalam bentuk kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah sepak bola, dan hingga kini masih menjadi ciri di liga-liga Eropa.
Bukti nyata, total football Belanda, atau kick and rush Inggris. Ada pun Italia dengan sepak bola pasif ala Catenaccio yang mengandalkan serangan balik, namun terbukti efektif mengantarkannya merebut tiga kali trofi Piala Dunia. Determinasi tinggi juga diperagakan oleh tim-tim semisal Jerman dan Prancis. Kolektivitas dan efisiensi permainan secara gemilang ditunjukkan oleh negeri para filsuf kuno, Yunani, dengan menjuarai Piala Eropa 2004 lalu, yang kini melaju di babak 16 besar
Ini jelas berbeda dengan gaya permainan tim-tim asal Amerika latin semisal Brazil dan Argentina yang cenderung memainkan jogo bonito -sebuah estetika bermain sepak bola yang menghibur dengan gerakan “menari-nari” di lapangan. Meski tidak memiliki tradisi filsafat yang kuat, namun tim-tim Amerika Latin mampu menggabungkan kultur tarian mereka dengan olahraga.
Maka jika dibandingkan, tak heran dribbling Thomas Mueller tidak seatraktif Lionel Messi. Van Persie tak selincah Neymar. Namun sedikit saja Mueller dan Persie mempunyai peluang, naluri gol pemain sekolahan ini tak kalah mematikan dengan dua pemain Brazil tersebut.
(*) Penulis adalah dosen di Universitas Airlangga dan Universitas Ciputra
(aww)