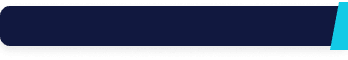Soeratin

Soeratin
A
A
A
"SETIAP Setiap generasi mendekap dan memeluk sejarahnya sendiri". Hindia Belanda atau yang kemudian disebut Indonesia, di kurun waktu tahun 1920 hinga 1930-an bisa bercerita membuktikan atau menyangkal adagium itu. Sejarah Indonesia 'muda' waktu itu sangat dikondisikan tertib, loyal, tak gaduh dan wajib patuh pada titah penguasa tertinggi, Kerajaan Belanda.
Ada garis demarkasi jelas antara siapa penguasa, siapa yang dikuasai. Siapa majikan, siapa tuan, siapa hamba, siapa sahaya, siapa juragan, siapa buruh. Siapa kelompok kulit putih meener Belanda, siapa kaum pribumi inlander. Pembedanya jelas. Sebuah sejarah khas dari negeri jajahan, negeri yang belum mengenal apa arti merdeka, arti kebebasan, arti bebas menentukan nasibnya sendiri.
Zaman itu Hindia Belanda memang tak ramah bagi kaum inlander yang mayoritas. Kaum yang dikuasai, kelompok hamba sahaya, kelompok marginal yang di sejumlah tempat menjadi kelas bawah, entah itu bernama buruh, petani, jongos, pekathik ataupun pesuruh. Yang pasti kaum inlander bersanding erat dengan steorotip golongan kaum bawah, bodoh, tak terdidik dan pemalas.
Beruntung, keluarga R. Sosrosoegondo bukan inlander. Sebagai keluarga priyayi, Sosrosoegondo tak perlu repot-repot menunduk dan mengucapkan sapaan ndoro ketika berpapasan dengan meneer Belanda ataupun kaum priyayi lain. Mereka juga hidup berkecukupan dan tak disibukkan dengan kerja paksa yang zaman itu banyak menjadi 'pekerjaan' utama kaum inlander.
Dalam keseharian, keluarga Sosrosoegondo tak perlu 'berkeringat', termasuk untuk urusan pendidikan. Dengan mudah pendidikan Barat dikecap anak-anak Sosrosoegondo, termasuk salah satu anaknya Soeratin. Ya, dalam nadi Soeratin muda memang mengalir deras darah biru keluarga besar priyayi R Sosrosoegondo. Darah priyayi itulah yang ikut membantunya menumbuhkan jiwa perlawanan terhadap Belanda dengan ikhtiarnya melalui sepak bola kelak.
Mengecap bangku sekolah menengah di sekolah priyayi di Koningen Wilhelmina School Jakarta, Soeratin muda tak sulit terbang ke mancanegara untuk melahap pendidikan teknik di Sekolah Teknik Tinggi Hecklenburg, dekat Hamburg, Jerman. Tujuh tahun cukup bagi Soeratin muda menggondol gelar insiyur di negeri Adolf Hitler tersebut. Tahun 1928, Soeratin kembali menginjak tanah air.
Syahdan, era tahun 1928-1930, bumi Indonesia begitu muram dan tak berdaya. Rezim Belanda terus sedang giat-giatnya menancapkan kuku kekuasaaanya hampir di semua bidang. Pribumi inlander dipaksa menjadi warga kelas dua di negerinya sendiri. Mendapati negerinya lunglai tak berdaya, jiwa Soeratin menjerit. Meski dibesarkan pendidikan Barat, sebagai anak bangsa jiwanya masygul menyaksikan sikap adigang, adigung dan adiguna penjajah.
Pekerjaan empuk di salah satu perusahaan konstruksi terkemuka milik Belanda pun ditanggalkan. Tekadnya bulat, tujuannya satu! Berusaha mencapai persatuan bangsanya sebagaimana nasionalisme Budi Oetomo yang dideklarasikan iparnya Dr Soetomo pada 1928. Sedikit berbeda dengan kebanyakan pemuda pejuang kala itu, Soeratin menjatuhkan pilihan ke bidang olahraga sebagai alat perjuangan membendung kekuasaan Belanda.
Siasat dan strategi pun diatur. Bersama kawan-kawannya, Soeratin mulai merintis membangun sebuah organisasi olahraga perlawanan. Cabang olahraga sepakraga yang mengandalkan kaki pun dipilih. Kendati tak mudah karena diawasi intel dan sisik melik Belanda, akhirnya pada 19 April 1930, bertempat di Yogyakarta lahirlah organ perjuangan bernama Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI). 'Bayi' organisasi inilah yang kelak 'dewasa' menjelma menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Pada kongres PSSI di Solo 1930, kata "Sepakraga" dalam PSSI diubah menjadi Sepak Bola. Sejak saat itulah PSSI mempelopori kompetisi sepak bola rutin yang digelar di sejumlah kota dengan berbagai klub peserta. Tak butuh waktu lama, sebagai alat perjuangan dan organisasi olahraga, PSSI dan kompetisinya bertambah besar dan merakyat.
Berkibarnya panji PSSI ternyata tak menyilaukan para pengurusnya. Sebagai pendiri sekaligus ketua selama 10 tahun sejak 1930 hingga 1940, Soeratin tetap istiqomah mengobarkan api perlawanan kepada Belanda melalui organ PSSI.
Tokoh dengan gagasan besar terkadang memang harus melalui jalan berliku dan berkelok dalam membumikan ide-idenya. Diktum ini juga yang pada akhirnya menerpa Soeratin dengan PSSI-nya. Terlahir dari keluarga berada dan merintis berdirinya sebuah alat perjuangan bangsa di bidang olahraga, Soeratin tua di massa senja justru harus tertatih-tatih dalam ketidakberdayaan.
Cengkraman dan tangan-tangan kuat Belanda terus membelenggu dan menggerus aktivitasnya. Soeratin pun harus menerima konsekuensi logis sebuah perjuangan kala itu yakni digerogoti persoalan ekonomi. Maklum, hampir semua harta dan kekayaannya tak tersisa demi membiayai PSSI. Soeratin pada akhirnya tak sempat melihat PSSI yang dibentuknya memberi kontribusi terhadap bangsa ini. Pada 1 Desember 1959, foundhing father organisasi olahraga yang berbasis pada kaki ini menutup mata untuk selama-lamanya dalam kesunyian.
"Setiap generasi menulis sejarahnya sendiri". Dan Soeratin dengan PSSI-nya telah mengawali membuat sejarah dari generasinya. Sejarah generasi PSSI era saat ini berbeda PSSI-nya Soeratin dulu. PSSI era Soeratin berjasa menyemai dan menyulam narasi sejarah bernama PSSI hingga saat ini. Menginjak usia 88 tahun, masihkan PSSI tetap mewarisi khittah sebagai alat perjuangan seperti halnya diinginkan Soeratin?
Wallahualam, Selamat Harlah PSSI ke-88*
Ada garis demarkasi jelas antara siapa penguasa, siapa yang dikuasai. Siapa majikan, siapa tuan, siapa hamba, siapa sahaya, siapa juragan, siapa buruh. Siapa kelompok kulit putih meener Belanda, siapa kaum pribumi inlander. Pembedanya jelas. Sebuah sejarah khas dari negeri jajahan, negeri yang belum mengenal apa arti merdeka, arti kebebasan, arti bebas menentukan nasibnya sendiri.
Zaman itu Hindia Belanda memang tak ramah bagi kaum inlander yang mayoritas. Kaum yang dikuasai, kelompok hamba sahaya, kelompok marginal yang di sejumlah tempat menjadi kelas bawah, entah itu bernama buruh, petani, jongos, pekathik ataupun pesuruh. Yang pasti kaum inlander bersanding erat dengan steorotip golongan kaum bawah, bodoh, tak terdidik dan pemalas.
Beruntung, keluarga R. Sosrosoegondo bukan inlander. Sebagai keluarga priyayi, Sosrosoegondo tak perlu repot-repot menunduk dan mengucapkan sapaan ndoro ketika berpapasan dengan meneer Belanda ataupun kaum priyayi lain. Mereka juga hidup berkecukupan dan tak disibukkan dengan kerja paksa yang zaman itu banyak menjadi 'pekerjaan' utama kaum inlander.
Dalam keseharian, keluarga Sosrosoegondo tak perlu 'berkeringat', termasuk untuk urusan pendidikan. Dengan mudah pendidikan Barat dikecap anak-anak Sosrosoegondo, termasuk salah satu anaknya Soeratin. Ya, dalam nadi Soeratin muda memang mengalir deras darah biru keluarga besar priyayi R Sosrosoegondo. Darah priyayi itulah yang ikut membantunya menumbuhkan jiwa perlawanan terhadap Belanda dengan ikhtiarnya melalui sepak bola kelak.
Mengecap bangku sekolah menengah di sekolah priyayi di Koningen Wilhelmina School Jakarta, Soeratin muda tak sulit terbang ke mancanegara untuk melahap pendidikan teknik di Sekolah Teknik Tinggi Hecklenburg, dekat Hamburg, Jerman. Tujuh tahun cukup bagi Soeratin muda menggondol gelar insiyur di negeri Adolf Hitler tersebut. Tahun 1928, Soeratin kembali menginjak tanah air.
Syahdan, era tahun 1928-1930, bumi Indonesia begitu muram dan tak berdaya. Rezim Belanda terus sedang giat-giatnya menancapkan kuku kekuasaaanya hampir di semua bidang. Pribumi inlander dipaksa menjadi warga kelas dua di negerinya sendiri. Mendapati negerinya lunglai tak berdaya, jiwa Soeratin menjerit. Meski dibesarkan pendidikan Barat, sebagai anak bangsa jiwanya masygul menyaksikan sikap adigang, adigung dan adiguna penjajah.
Pekerjaan empuk di salah satu perusahaan konstruksi terkemuka milik Belanda pun ditanggalkan. Tekadnya bulat, tujuannya satu! Berusaha mencapai persatuan bangsanya sebagaimana nasionalisme Budi Oetomo yang dideklarasikan iparnya Dr Soetomo pada 1928. Sedikit berbeda dengan kebanyakan pemuda pejuang kala itu, Soeratin menjatuhkan pilihan ke bidang olahraga sebagai alat perjuangan membendung kekuasaan Belanda.
Siasat dan strategi pun diatur. Bersama kawan-kawannya, Soeratin mulai merintis membangun sebuah organisasi olahraga perlawanan. Cabang olahraga sepakraga yang mengandalkan kaki pun dipilih. Kendati tak mudah karena diawasi intel dan sisik melik Belanda, akhirnya pada 19 April 1930, bertempat di Yogyakarta lahirlah organ perjuangan bernama Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI). 'Bayi' organisasi inilah yang kelak 'dewasa' menjelma menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Pada kongres PSSI di Solo 1930, kata "Sepakraga" dalam PSSI diubah menjadi Sepak Bola. Sejak saat itulah PSSI mempelopori kompetisi sepak bola rutin yang digelar di sejumlah kota dengan berbagai klub peserta. Tak butuh waktu lama, sebagai alat perjuangan dan organisasi olahraga, PSSI dan kompetisinya bertambah besar dan merakyat.
Berkibarnya panji PSSI ternyata tak menyilaukan para pengurusnya. Sebagai pendiri sekaligus ketua selama 10 tahun sejak 1930 hingga 1940, Soeratin tetap istiqomah mengobarkan api perlawanan kepada Belanda melalui organ PSSI.
Tokoh dengan gagasan besar terkadang memang harus melalui jalan berliku dan berkelok dalam membumikan ide-idenya. Diktum ini juga yang pada akhirnya menerpa Soeratin dengan PSSI-nya. Terlahir dari keluarga berada dan merintis berdirinya sebuah alat perjuangan bangsa di bidang olahraga, Soeratin tua di massa senja justru harus tertatih-tatih dalam ketidakberdayaan.
Cengkraman dan tangan-tangan kuat Belanda terus membelenggu dan menggerus aktivitasnya. Soeratin pun harus menerima konsekuensi logis sebuah perjuangan kala itu yakni digerogoti persoalan ekonomi. Maklum, hampir semua harta dan kekayaannya tak tersisa demi membiayai PSSI. Soeratin pada akhirnya tak sempat melihat PSSI yang dibentuknya memberi kontribusi terhadap bangsa ini. Pada 1 Desember 1959, foundhing father organisasi olahraga yang berbasis pada kaki ini menutup mata untuk selama-lamanya dalam kesunyian.
"Setiap generasi menulis sejarahnya sendiri". Dan Soeratin dengan PSSI-nya telah mengawali membuat sejarah dari generasinya. Sejarah generasi PSSI era saat ini berbeda PSSI-nya Soeratin dulu. PSSI era Soeratin berjasa menyemai dan menyulam narasi sejarah bernama PSSI hingga saat ini. Menginjak usia 88 tahun, masihkan PSSI tetap mewarisi khittah sebagai alat perjuangan seperti halnya diinginkan Soeratin?
Wallahualam, Selamat Harlah PSSI ke-88*
(amm)